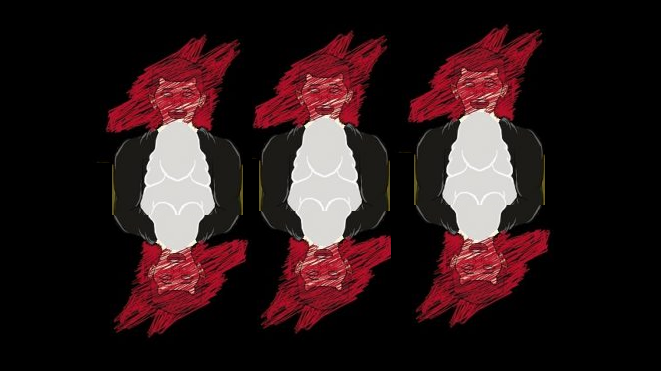Aku tak akan menghampiri rumah si Kerudung Merah jika bukan karena hantu ayahku; ia mati sepuluh tahun lalu dengan perut penuh bebatu.
Ayahku serigala yang baik—setidaknya semasa ia hidup. Waktu itu di hutan sedang sepi hewan buruan, para manusia pemburu lebih cepat membabat rusa dan kijang dan apa pun yang bisa kami makan, dan Ayah memberikan kesemua jatah makanannya untuk aku yang terus menangis karena kelaparan di gua. Dan setelah aku terlelap saking kenyangnya, Ayah berkeliling hutan mencari makanan untuk dirinya, dan ia menemukan seorang gadis berkerudung merah, gadis yang membawa berbagai kue dan beberapa botol anggur dalam keranjang untuk nenek yang sakit, dan Ayah tak tahu bahwa gadis selugu itu dapat membawa maut padanya. Seusai menceritakan tentang kematiannya untuk kali pertama padaku, beberapa jam setelah maut datang padanya, hantu Ayah berkata, “Saat besar nanti, kau akan memasukkan batu-batu ke perut gadis itu.” Setelah itu hantu Ayah pergi, kupikir untuk selama-lamanya.
Kini hantu Ayah kembali padaku, setelah sepuluh tahun tak pernah muncul; ia mengatakan Ibu si Kerudung Merah sedang sekarat, “Dan perutnya menunggu batu-batuan.” Kupikir harusnya aku memasukkan batu-batu ke perut si Kerudung Merah, bukan ke perut ibunya. Namun hantu Ayah ingin pembalasan dendamnya lebih dahsyat: aku tetap harus memasukkan batu-batu ke perut si Kerudung Merah setelah perut ibunya, entah di hari yang sama atau hari yang lain.
Aku bukan serigala pendendam, jadi kuusir saja hantu Ayah dari guaku; aku ingin menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anakku, aku ingin fokus membentuk koloni baru, aku ingin fokus menyelamatkan koloniku dari para manusia pemburu. Tetapi tak ada hantu pendendam yang suka melihat anaknya menjadi bukan pendendam: saban tidur aku selalu bermimpi buruk, dan kuyakin hantu Ayah-lah yang memasukkan mimpi itu menuju kepalaku.
Aku melihat Ayah tidur nyenyak di kasur di sebuah rumah kayu, itu pasti rumah Nenek si Kerudung Merah; perut Ayah buncit dan ia mengenakan pakaian wanita tua tersebut, tiba-tiba seorang pemburu memasuki kamar itu dengan terkejut. Pemburu itu buru-buru menenangkan diri, ia mengeluarkan gunting dan membelah perut ayahku, serigala itu tak terbangun mungkin sebab ia terlalu kenyang, dan dari perutnya keluarlah si Kerudung Merah serta neneknya, tubuh mereka basah oleh cairan asam. Lalu si Kerudung Merah berlari keluar rumah sejenak, sebelum kembali dengan batu-batuan dalam dekapannya yang penuh, dan ia memasukkan bebatu ke perut ayahku, sebelum menjahit perut serigala malang itu dengan rapi dan rapat. Kemudian tibalah bagian mengerikan itu: si Kerudung Merah membangunkan Ayah, serigala itu terkejut dan langsung berlari keluar sembari menahan sakit, dan aku dapat merasakan betul kesakitan dalam perutnya yang berat, seakan akulah yang berlari di sana dengan perut penuh bebatu. Akhirnya Ayah tumbang di setapak hutan dan napasku terasa memberat, terasa tercekik—perutku terasa akan dirobek dari dalam![1]
Mimpi itu tak datang sekali; ia datang setiap aku tidur; rasa sakit tetap bertahan pada perutku bahkan berjam-jam setelah aku terjaga, dan aku tersadar: hantu Ayah benar-benar mendendam pada si Kerudung Merah—jangan sampai mendendam juga ia padaku, karena penolakanku untuk membalaskan dendamnya.
***
Rumah keluarga si Kerudung Merah berdiri di tepi hutan dan malam itu aku menyusup ke semak-semak di halaman belakang, lalu melalui celah gorden aku melihat wanita tua itu mengerang di ranjang, si Kerudung Merah menyuapinya sesuatu, dan dari tatapannya kutahu ia berharap tak perlu lagi menyuapinya apa pun. Mereka hanya tinggal berdua di situ—entah ke manakah ayah si Kerudung Merah. Ketika sang ibu terlelap dan lampu dipadamkan dan si Kerudung Merah keluar dari kamar itu, diam-diam aku membuka jendela dan menyusup dengan batu-batu memenuhi dekapanku.
Dari wanita itu menyeruak aroma tahi. Selimutnya pada bagian kaki tersibak sedikit dan dari sanalah aroma itu menyeruak. Aku menatap sekeliling dan cahaya bulan yang masuk dari lubang udara jatuh ke cermin; aku melihat wajahku di sana, mataku tak pernah semerah itu: mesti itu sepasang mata serigala yang sedang di bawah pengaruh hantu pendendam. Di samping cermin terdapat sebuntal benang jahit di atas meja, jarum-jarum menancap pada buntalan itu, pentul-pentul merahnya berkilau tertimpa cahaya bulan.
Aku menyibak selimut sang wanita perlahan; ia mengenakan daster biru dan roknya terangkat hampir sampai ke pinggul, popoknya kembung dan aroma tahi merobek lubang hidungku. Mungkin ini kutukan hewan berpenciuman tajam: kami agak lemah di hadapan wanita sekarat yang berak di popok. Tapi tak ada waktu untuk kalah dari tahi di popok; aku menaikkan dasternya sampai sedada, kulit perutnya begitu tipis, aku hampir dapat melihat jeroannya di balik sana, yang berdenyut-denyut memompa tahi. Kuku telunjukku mencuat, dan dengan hati-hati aku menyayat perut wanita itu secara vertikal, wanita itu tak terbangun mungkin sebab terlalu kenyang, dan aroma jeroannya bahkan lebih terkutuk ketimbang tahinya. Lalu aku memasukkan batu-batu ke dalam perutnya, satu per satu dan penuh kehati-hatian, aku—dan ayahku—tak mau ia terbangun tidak pada waktunya. Dan setelah kesemua batu kumasukkan, aku mengambil sebuntal benang di meja dan menjahit perutnya serapi-serapat mungkin, dan ia tampak persis wanita hamil yang mengandung mautnya sendiri.
Sesaat aku ragu untuk membangunkannya; toh, ia akan mati tanpa kubangunkan—aku bisa mendengar napasnya yang semakin lama semakin berat. Tetapi ketika aku melirik ke cermin lagi, bukan saja sepasang mataku semakin merah, aku melihat hantu Ayah berdiri di belakangku, ia mendekatkan moncongnya ke kupingku, ia berbisik, “Jangan lewatkan bagian yang paling seru.”
Aku menjilat darah di kuku telunjuk, dan aku menyalakan lampu, dan aku mengguncang-guncang kasur, tetapi wanita itu tak terbangun. Aku menampar-nampar pipinya, dan ia hanya berkedip lemah sebelum kembali tertidur. Akhirnya aku menyiram wajahnya dengan air dari teko di nakas, dan ia pun terbelalak di hadapan taring-taringku. Ia segera menjerit dan berguling dari kasur. Ia tak sanggup berdiri, tentu saja; aku melangkah ke sampingnya dan ia tetap memekik dan ia tetap terbaring di lantai dan ia akan mati seperti itu.
Pintu dibuka: si Kerudung Merah menodongkan senapan padaku. Moncong senapannya terus menatapku lekat, tetapi perempuan itu berganti-gantian menatapku dan sang ibu yang perutnya penuh bebatu. Aku berpaling ke cermin: mataku tak lagi merah, dan hantu Ayah tak ada di mana pun. Ia hanya ingin melihat Ibu si Kerudung Merah mati; ia tak berani melihatku mati. Setidaknya mati di ujung senapan jauh lebih baik ketimbang mati dengan perut penuh bebatu.
Dan tiba-tiba senapan meletus.
Tubuhku masih utuh. Tapi perut wanita itu terkoyak peluru—batu-batu di dalam sana terlihat, dan dari batu-batu itu pandangan si Kerudung Merah teralih padaku. Aku tak tahu arti tatapannya. Kemudian ia meletakkan senapan di lantai, ia mendekati mayat ibunya—aku menyingkir agar tak menghalanginya—dan ia mencoba membopongnya ke kasur. Baru terangkat sedikit, ia langsung menjatuhkan tubuh wanita itu. Ia mencoba hal serupa dua kali lagi dan gagal, lantas ia memasukkan tangan ke lubang peluru di perut ibunya, ia mengambil segenggam batu dan dengan gerakan cepat melemparnya ke kepalaku.
Dahiku hangat. Aku menyentuhnya dan darah tercetak pada rambut di telapak tanganku. Kupikir sebentar kemudian darah akan mengguyur mata dan moncongku, tetapi tidak—kepalaku tak berdarah dan yang ada di tanganku hanyalah darah yang menempel di batu itu.
“Bisa bantu aku …?” ucap si Kerudung Merah.
Kami pun bersama-sama mengangkat mayat ke kasur, dan gadis itu menutupi sekujur tubuh sang ibu dengan selimut biru yang dengan cepat memerah. Gadis itu menunduk dan menggumamkan sesuatu, barangkali ia berdoa. Ketika keseluruhan selimut memerah dan basah, bentuk mayat itu tercetak jelas pada selimut.
Si Kerudung Merah memungut senapannya. Ia tak menembakku; ia menyampirkannya di pundak. Dan, sepasang matanya memerah; sepasang matanya menatapku lekat. Tetapi aku masih tak tahu apa arti tatapannya; aku hanya tahu itu tatapan manusia yang terluka—tak beda jauh dengan tatapan hewan yang terluka—dan ia mengangguk padaku, sebelum ia keluar dari kamar ibunya. “Sampai jumpa lagi,” kata si Kerudung Merah dari balik pintu, suaranya parau.
Aku mematikan lampu, dan aku keluar lewat jendela, dan aku kembali ke guaku. Aku tak berminat memasukkan batu-batu ke perut si Kerudung Merah. Lebih baik aku memasukkan batu-batu ke perut hantu ayahku ketimbang ke perut perempuan itu. Tetapi perut hantu tak bisa dibelah, dan hantu pendendam tak berhenti mengirim mimpi buruk padaku. Aku mulai terbiasa dengan sakit yang melekat bahkan berjam-jam setelah aku terjaga. Sakit itu tak seberapa ketimbang rasa bersalahku sebab memasukkan bebatu ke perut wanita itu.
Semoga si Kerudung Merah tak bermimpi buruk. Semoga ia tak memimpikan kesakitan terakhir sang ibu.
[1] Bagian tragis yang menimpa Ayah si Serigala ini adalah akhir dari Little Red Riding Hood versi Grimm bersaudara; beberapa pengarang lain mempunyai versi akhir cerita yang lain.
*) Cerpen ini dimuat di Tatkala.co pada 26 Februari 2022.